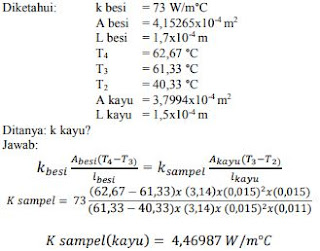Telah
dilakukan pecobaan tentang pengukuran daya satu fasa
dengan tujuan untuk mempelajari cara pengukuran daya listrik satu
fasa dengan cara tiga amperemeter dan dengan cara tiga voltmeter.
Percobaan dilakukan dalam dua rangkaian. Pada percobaan pertama
yaitupengukuran daya listrik satu fasa dengan cara tiga amperemeter
dilakukan dengan mengubah tegangan sumbernya (5V, 10V, 15V, 20V, 25V,
30V) kemudian didapatkan data besar arus I1,
I2, I3yang kemudan
dapat dihitung untuk nilai daya listrik satu fasanya dengan
persamaan(2). Dengan hambatan
penggantinya adalah disusun secara parallel yang nilainya 100.288Ω.
Percobaan kedua yaitu pengukuran daya listrik satu fasa
dengan cara tiga voltmeter dilakukan dengan mengubah tegangan
sumbernya (5V, 10V, 15V, 20V, 25V, 30V) kemudian didapatkan data
besar arus V1, V2,
V3 yang kemudan dapat dihitung untuk nilai
daya listrik satu fasanya dengan persamaan (3). Dari
hasil percobaan didapat daya
satu fasa rata-rata yang didapatkan dengan metode tiga ampermeter
yaitu 1,09778 Watt dan daya satu fasa rata-rata yang didapatkan
dengan metode tiga voltmeter yaitu 0,1505 Watt.Dari
kedua cara pengukuran daya
yaitu dengan cara tiga ampermeter dan tiga
voltmeter didapatkan hasil perhitungan
daya listrik satu fasa antara
menggunakan tiga amperemeter
dan tiga voltmeter menunjukkan hasil
yang berbeda.Hal
ini dikarenakan factor keefektifan rangkaian yang digunakan. Pada
percobaan ini rangkaian yang lebih efektif yaitu dengan metode tiga
amperemeter.Daya listrik satu fasa yang
dihasilkan dengan metode tiga amperemeter menunjukkan hasil yang
lebih besar daripada dengan menggunakan metode tiga voltmeter.Dari
keadaan ini terdapat jenis daya yang dipakai diantaranya daya semu,
daya sesaat dan sebagainya
yang memungkinkan pengukuran mempunyai hasil pengukuran yang kurang
efektif.
I. PENDAHULUAN
Daya
listrik didefinisikan sebagai laju hantaran energi listrik dalam
rangkaian listrik. Satuan SI daya listrik adalah watt. Arus listrik
yang mengalir dalam rangkaian dengan hambatan listrik menimbulkan
kerja. Peranti mengkonversi kerja ini ke dalam berbagai bentuk yang
berguna, seperti panas (seperti pada pemanas listrik), cahaya
(seperti pada bola lampu), energi kinetic (motor listrik), dan suara
(loudspeaker). Listrik dapat diperoleh dari pembangkit listrik atau
penyimpan energi seperti baterai[2].
Daya
listrik, seperti daya mekanik, dilambangkan oleh huruf P dalam
persamaan listrik. Pada rangkaian arus DC, daya listrik sesaat
dihitung menggunakan Hukum Joule, sesuai nama fisikawan Britania
James Joule, yang pertama kali menunjukkan bahwa energi listrik dapat
berubah menjadi energy mekanik, dan sebaliknya.
....................................................................................................................................................................................................(1)
Dimana
P adalah daya (watt atau W), I adalah arus (ampere atau A),V adalah
perbedaan potensial (volt atau V)[3].
Gambar
1 Segitiga Daya
Impedansi
Z dalam hal ini dapat terdiri dari berbagai jenis beban resistif,
induktif, kapasitif ataupun kombinasi dari ketiga jenis beban
sehingga sebuah impedansi Z yang memiliki karakteristik gabungan dari
karakteristik berbagai jenis beban yang menyusunnya. Yang dimaksud
dengan karakteristik beban adalah jenis daya yang diserapnya, sifat
arus dan tegangannya yang bila digabungkan dengan jenis beban yang
berbeda dapat terbentuk karakteristik yang lebih baik maupun lebih
buruk (jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda). Pada
pengukuran daya, ada juga yang dikenal dengan faktor daya, yaitu
perbandingan antara daya aktif (Watt) dengan daya semu (VA), atau
cosinus sudut antara daya aktif dan daya semu. cosφ=P/S[2].
Faktor
daya atau faktor kerja adalah perbandingan antara daya aktif (watt)
dengan daya semu/daya total (VA), atau cosinus sudut antara daya
aktif dan daya semu/daya total (lihat gambar 1). Daya reaktif yang
tinggi akan meningkatkan sudut ini dan sebagai hasilnya faktor daya
akan menjadi lebih rendah. Faktor daya selalu lebih kecil atau sama
dengan satu. Secara teoritis, jika seluruh beban daya yang dipasok
oleh perusahaan listrik memiliki faktor daya satu, maka daya maksimum
yang ditransfer setara dengan kapasitas sistim pendistribusian.
Sehingga, dengan beban yang terinduksi dan jika faktor daya berkisar
dari 0,2 hingga 0,5, maka kapasitas jaringan distribusi listrik
menjadi tertekan. Jadi, daya reaktif (VAR) harus serendah mungkin
untuk keluaran kW yang sama dalam rangka meminimalkan kebutuhan daya
total (VA). Faktor Daya / Faktor kerja menggambarkan sudut phasa
antara daya aktif dan daya semu. Faktor daya yang rendah merugikan
karena mengakibatkan arus beban tinggi. Perbaikan faktor daya ini
menggunakan kapasitor[1].
II.
METODE
Dalam percobaan
pengukuran daya satu fasa dilakukan dengan dua rangkaian percobaan.
Untuk percobaan pertama yaitu dengan metode tiga amperemeter. Kedua,
yaitu dengan metode tiga voltmeter. Untuk percobaan ini digunakan
alat seperti Vari AC, Voltmeter, Amperemeter, Induktor, Resistor dua
buah, Kabel Buaya.
Percobaan pertama
yaitu mengukur daya listrik satu fasa dengan metode tiga
amperemeter.Langkah awal yang dilakukan
yaitu resistor, beban(R+L), ampermeter dan Vari AC
disusun sehingga membentuk suatu
rangkaian percobaan seperti pada gambar 1. Setelah rangkaian
tersusun,, Vari AC dinyalakan dan diatur tegangan sumbernya ( 5V ,10V
,15V ,20V ,25V ,30V ). Selanjutnya diukur nilai arus A1, A2, A3 pada
ampermeter. Percobaan diulangi dengan tegangan sumber yang berbeda (
5V ,10V ,15V ,20V ,25V ,30V ). Pada percobaan yang pertama didapatkan
nilai arus I1, I2, I3untuk
masing-masing tegangan yang berbeda.
Gambar
(1) Rangkaian percobaan dengan metode tiga amperemeter
Dari tujuan
percobaan yaitu mempelajari cara mengukur daya listrik satu fasa
dengan cara tiga amperemeter, maka untuk dapat menentukaan nilai daya
listrik tersebut dapat digunakan persamaan
sebagai berikut :
....................................................................................................................................................................................................(2)
dimana, P adalah
daya yang dicari nilainya, R adalah hambatan pengganti rangkaian, dan
I adalah arus listrik yang telah didapat dari percobaan.
Pada
percobaan yang kedua yaitu mengukur daya listrik satu fasa
dengan metode tiga voltmeter. Dalam percobaan ini
langkah awal yang dilakukan adalah
resistor, beban(R+L), voltmeter dan Vari AC
disusun sehingga membentuk suatu
rangkaian percobaan seperti pada gambar 2 .Setelah rangkaian
tersusun,, Vari AC dinyalakan dan diatur tegangan sumbernya atau V1
( 5V ,10V ,15V ,20V ,25V ,30V ). Selanjutnya diukur nilai tegangan V2
dan V3 pada voltmeter. Percobaan diulangi dengan tegangan sumber yang
berbeda ( 5V ,10V ,15V ,20V ,25V ,30V ). Pada percobaan yang kedua
ini didapatkan nilai tegangan V2 dan V3 untuk masing-masing tegangan
sumber atau V1 yang berbeda.
Gambar
(2) Rangkaian percobaan dengan metode tiga Voltmeter
Dari tujuan
percobaan yaitu mempelajari cara mengukur daya listrik satu fasa
dengan cara tiga voltmeter, maka untuk dapat menentukaan nilai daya
listrik tersebut dapat digunakan persamaan
sebagai berikut :
....................................................................................................................................................................................................(3)
dimana, P adalah
daya yang dicari nilainya, R adalah hambatan pengganti rangkaian, dan
V adalah tegangan yang telah didapat dari percobaan.
III. HASIL DAN
PEMBAHASAN
Dengan Metode Tiga Amperemeter
Percobaan
yang pertama bertujuan untuk mempelajari cara mengukur daya
satu fasa dengan metode tiga amperemeter. Sehingga
untuk mendapatkan daya listrik satu fasa
dapat dilakukan dengan perhitungan menggunakan persamaan(2) .
Sumber tegangan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu
sumber tegangan AC dengan variasi tegangan
sumber sebesar 5V ,10V ,15V ,20V ,25V ,30V. Resistor (R) yang
digunakan bernilai 330 Ω dan beban (Z) yang digunakan adalah
Induktor 330 mH dan Resistor 100Ω sehingga nilai beban Z adalah
144,07169 . Untuk R pengganti yang digunakan yaitu dihitung secara
paralel (gambar 2). Dari percobaan diperoleh data
arus I1, I2, I3 .Sehingga
dapat dihitung nilai daya listrik satu fasanya.
Dibawah ini adalah hasil dari percobaan dan
perhitungan daya listrik satu fasa yang dihasilkan dalam
percobaan ini.
Tabel 1Data
nilai I1, I2, I3 dan
Perhitungan Daya Listrik Satu Fasa
No.
|
V(Volt)
|
I1(A)
|
I2(A)
|
I3
(A)
|
R
(Ω)
|
P(W)
|
1
|
5.166
|
0.064
|
0.048
|
0.015
|
100.288
|
0.079
|
2
|
10
|
0.124
|
0.094
|
0.029
|
100.288
|
0.286
|
3
|
15.09
|
0.19
|
0.142
|
0.045
|
100.288
|
0.698
|
4
|
20.07
|
0.25
|
0.19
|
0.059
|
100.288
|
1.149
|
5
|
25.09
|
0.313
|
0.237
|
0.074
|
100.288
|
1.821
|
6
|
30.07
|
0.371
|
0.281
|
0.088
|
100.288
|
2.554
|
Pada tabel hasil percobaan diatas dapat dianalisis bahwasemakin besar teganagan yang diberikan maka arusnya juga semakin membesar. Dapat dianalisa bahwa data diatas menunjukkanarus yang masuk pada rangkaiansama dengan total arus yang keluar rangkaian. Hasil dari percobaan ini sesuai dengan Hukum Arus Kirchoff yang menyatakan bahwa besarnya arus yang masuk pada rangkaian sama dengan besar arus yang keluar rangkaian .
Selain itu juga dapat dilihat bahwa daya listrik satu fasa yang dihasilkan semakin bertambah seiring bertambahnya tegangan sumber yang diberikan dan arus yang mengalir pada rangkaian. Dalam percobaan ini daya rata-rata yang diperoleh adalah 1,09778 Watt.
Dengan Metode Tiga Voltmeter
Percobaan
yang keduabertujuan untuk mempelajari cara mengukur daya satu
fasa dengan metode tiga voltmeter. Sehingga untuk
mendapatkan daya listrik satu fasa dapat
dilakukan dengan perhitungan menggunakan persamaan(3) .
Sumber tegangan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu
sumber tegangan AC dengan variasi tegangan
sumber sebesar 5V ,10V ,15V ,20V ,25V ,30V. Resistor (R) yang
digunakan bernilai 330 Ω dan beban (Z) yang digunakan adalah
Induktor 330 mH dan Resistor 100Ω sehingga nilai beban Z adalah
144,07169 . Untuk R pengganti yang digunakan yaitu dihitung secara
seri (gambar 3).Dalam percobaan ini diperoleh data
teganganV1, V2, V3 .Sehingga
dapat dihitung nilai daya listrik satu fasanya.
Dibawah ini adalah hasil dari percobaan dan
perhitungan daya listrik satu fasa yang dihasilkan dalam
percobaan kedua.
Tabel 2Data
nilai V1, V2, V3 dan
Perhitungan Daya Listrik Satu Fasa
No.
|
V
(Volt)
|
V1
(Volt)
|
V2
(Volt)
|
V3
(Volt)
|
R(Ω)
|
P(W)
|
1
|
5.07
|
5.07
|
3.93
|
1.16
|
474.072
|
0.0094
|
2
|
10.06
|
10.06
|
7.64
|
2.3
|
474.072
|
0.0396
|
3
|
15
|
15
|
11.42
|
3.44
|
474.072
|
0.08728
|
4
|
20.08
|
20.08
|
15.2
|
4.6
|
474.072
|
0.15927
|
5
|
25.09
|
25.09
|
18.98
|
5.59
|
474.072
|
0.25104
|
6
|
30.01
|
30.01
|
22.7
|
6.87
|
474.072
|
0.35661
|
Pada
tabel hasil percobaan diatas dapat dianalisis bahwa nilai V1
hampir mendekati nilai penjumlahan dari V2 dan V3.
Hal ini sesuai dengan Hukum Tegangan Kirchoff yang menyatakan bahwa
jumlah tegangan tiap komponen pada
sebuah loop sama dengan nol.
Selain
itu juga dapat dianalisis bahwa daya listrik satu fasa yang
dihasilkan semakin bertambah seiring bertambahnya tegangan sumber
yang diberikan.Dalam percobaan ini daya rata-rata yang diperoleh
adalah 0,1505 Watt.
Dari
kedua metode yang telah dilakukan dengan
menggunakan metode tiga amperemeter dan tiga voltmeter daya yang
diperoleh akan semakin besar jika tegangan sumber yang diberikan juga
semakin besar.Percobaan ini menunjukkan kesesuaian dengan
teori yang menyatakan bahwa daya itu sebanding dengan tegangan. Dari
kedua cara pengukuran daya yaitu dengan
cara tiga ampermeter dan tiga
voltmeterdidapatkan data hasil percobaan
yang berbeda. Hasil perhitungan
daya listrik satu fasa antara menggunakan
tiga amperemeter dan tiga voltmeter juga
menunjukkan hasil yang berbeda.
Daya yang didapatkan dengan metode tiga ampermeter yaitu
0.078576W; 0.28577W; 0.697552W; 1.149249W;
1.821429W; 2.554132W. Sedangkan daya yang didapatkan dengan
metode tiga ampermeter yaitu 0.0094W; 0.0396W;
0.08728W; 0.15927W; 0.25104W; 0.35661W.Dapat dianalisa bahwa daya
satu fasa yang dihasilkan dengan metode tiga amperemeter menunjukkan
hasil yang lebih besar daripada dengan menggunakan metode tiga
voltmeter.Hal ini mungkin karena factor keefektifan suatu rangkaian
dimana dalam hal ini rangkaian dengan metode tiga amperemeter lebih
efektif dimana pada rangkaian tiga amperemeter, hambatan disusun
secara parallel sedangkan pada rangkaian 3 voltmeter hambatan yang
digunakan disusun secara seri sehingga hal tersebut mempengaruhi
nilai hambatan pengganti dimana nilai hambatan yang disusun parallel
lebih kecil daripada hambatan yang disusun seri , sehingga daya yang
dihasilkan juga lebih besar pada percobaan dengan metode tiga
amperemeter daripada dengan metode tiga voltmeter.Dari
keadaan ini terdapat jenis daya yang dipakai diantaranya daya semu,
daya sesaat dan sebagainya yang
memungkinkan pengukuran mempunyai hasil pengukuran yang kurang
efektif.
IV.
KESIMPULAN
Dari
hasil percobaan dapat ditarik kesimpulan bahwa daya satu fasa
rata-rata yang didapatkan dengan metode tiga ampermeter yaitu1,09778
Watt. Sedangkan dayasatu fasa rata-rata
yang didapatkan dengan metode tiga voltmeter yaitu 0,1505 Watt.Dari
kedua cara pengukuran daya yaitu dengan
cara tiga ampermeter dan tiga voltmeter
didapatkan hasil perhitungan
daya listrik satu fasa antara menggunakan
tiga amperemeter dan tiga voltmeter
menunjukkan hasil yang berbeda.Hal
ini dikarenakan factor keefektifan rangkaian yang digunakan. Pada
percobaan ini rangkaian yang lebih efektif yaitu dengan metode tiga
amperemeter.Daya listrik satu fasa yang
dihasilkan dengan metode tiga amperemeter menunjukkan hasil yang
lebih besar daripada dengan menggunakan metode tiga voltmeter.Dari
keadaan ini terdapat jenis daya yang dipakai diantaranya daya semu,
daya sesaat dan sebagainya yang
memungkinkan pengukuran mempunyai hasil pengukuran yang kurang
efektif.
DAFTAR PUSTAKA
[1] Dosen Teknik
Elektro UI.Modul Praktikum Pengukuran Besaran Listrik.
Jakarta:UI-Press,2006
[2]Douglas Giancoli,
C. Fisika Jilid 1. Jakarta: Erlangga, 2001
[3]Serway&Jewett
. Physics for Scientist and Engineer. California:Thomson books,2004.